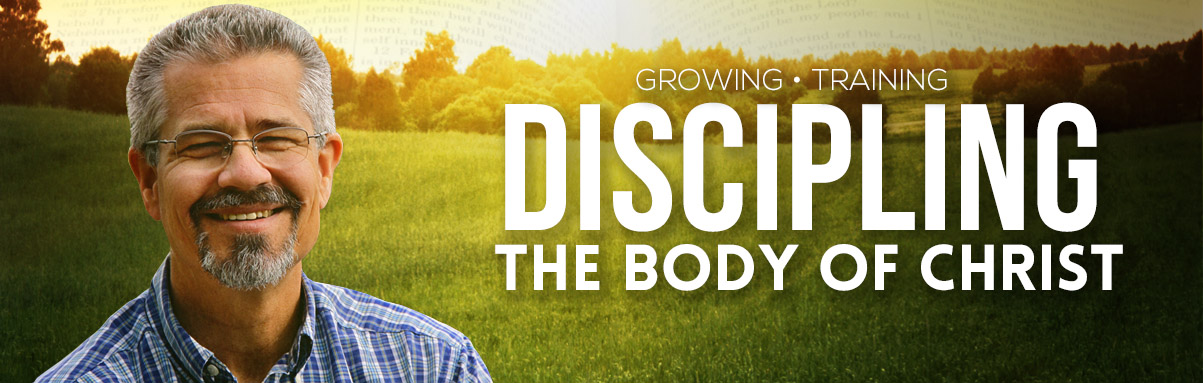Masalah perceraian dan pernikahan kembali sering diperdebatkan di kalangan orang-orang Kristen yang tulus hati. Ada dua pertanyaan penting sebagai dasar perdebatan itu, yakni: (1) Bila pernah, kapankan perceraian diizinkan di mata Allah?, dan (2) Bila pernah, kapan pernikahan kembali diizinkan di mata Allah? Sebagian besar denominasi dan gereja-gereja independen memiliki pendirian doktrin resmi tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh, sesuai penafsiran tertentu tentang Alkitab. Kita harus hargai setiap denominasi dan gereja karena masing-masing memiliki ketetapan-ketetapannya dan kita hidup dari semua ketetapan itu —asalkan semuanya termotivasi oleh kasih akan Allah. Tetapi, yang terbaik adalah jika kita memandang semua ketetapan itu 100% berdasarkan Alkitab. Pelayan pemuridan tidak ingin mengajarkan hal yang bukan kehendak Allah. Pelayan itu juga tidak ingin membebani orang-orang yang Allah tak ingin mereka pikul. Mengingat tujuan itu, saya akan lakukan sebaik-baiknya untuk Alkitab terkait dengan topik yang kontroversial dan anda sendiri yang memutuskan apakah setuju atau tidak setuju.
Saya mulai dengan berkata bahwa saya, seperti anda juga, merasa pedih melihat perceraian yang tak terkendali di dunia kini. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak orang yang mengaku Kristen bercerai, termasuk para pelayan. Ini tragedi besar. Kita perlu berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah agar tak terjadi lagi perceraian, dan solusi terbaik bagi perceraian adalah kabarkan Injil dan serukan pertobatan. Ketika pasangan suami-istri dilahirkan kembali dan mengikuti Kristus, mereka tak akan pernah bercerai. Pelayan pemuridan akan berbuat apa saja untuk tetap mempertahankan pernikahan, dan ia tahu bahwa contoh yang ia lakukan menjadi sarana mengajar yang paling berpengaruh.
Juga, saya sudah menikah lebih dari duapuluh-lima tahun dan sebelumnya belum pernah menikah. Saya tak dapat bayangkan tentang perceraian. Sehingga saya tak punya motif untuk melunakkan ayat-ayat Alkitab tentang perceraian untuk kepentingan sendiri. Tetapi, saya bersimpati kepada orang yang diceraikan, dan saya tahu bahwa saya bisa saja membuat keputusan buruk sebagai orang muda, dengan menikahi orang yang mungkin mencobai saya untuk bercerai, atau orang lain yang kurang toleran kepada saya dibandingkan wanita istimewa yang saya nikahi. Dengan kata lain, saya bisa saja bercerai, tetapi saya tak lakukan itu oleh karena kasih karunia Allah. Saya mau sebagian besar pasangan nikah untuk memperhatikan ucapan saya, sehingga kita perlu menahan diri agar tidak menyudutkan orang yang diceraikan. Dengan pernikahan yang kurang terjaga, siapakah kita sehingga mengecam orang-orang yang bercerai, tanpa memikirkan perkara yang mungkin telah mereka upayakan? Allah bisa saja menganggap mereka lebih benar dari kita, ketika Ia tahu bahwa kita bisa saja telah bercerai pada keadaan seperti itu.
Tak seorangpun yang sudah menikah mengharapkan perceraian, dan saya sangsi apakah ada orang yang membenci perceraian lebih dari orang yang telah menderita karena perceraian. Sehingga kita harus bantu orang-orang yang sudah menikah untuk menjaga ikatan pernikahan, dan membantu orang yang bercerai untuk mendapatkan apa yang dapat diberikan oleh kasih karunia Allah. Dengan semangat itu, saya membuat tulisan ini.
Saya akan berbuat semaksimal mungkin agar Alkitab menafsirkan Alkitab. Saya perhatikan ayat-ayat tentang topik perceraian yang sering ditafsirkan sehingga dipertentangkan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab, dan menjadi indikasi pasti bahwa ayat-ayat itu sudah dipahami, paling tidak sebagian.
Fondasi (A Foundation)
Kita mulai dengan kebenaran mendasar agar kita semua bisa sepaham. Yang paling mendasar, Alkitab tegaskan bahwa Allah sangat menentang perceraian. Selama beberapa pria Israel menceraikan istri mereka, Allah menyatakan melalui nabi Maleaki:
Sebab Aku membenci perceraian , ….. juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, ……Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat! (Maleakhi 2:16).
Tak mengejutkan bagi siapapaun yang tahu sesuatu tentang karakter Allah yang penuh kasih dan keadilan, atau siapapun yang tahu sesuatu tentang bagaimana perceraian berakibat buruk kepada suami, istri dan anak-anak. Kita harus tanyakan tentang karakter moral dari siapapun yang mendukung perceraian. Allah adalah kasih (lihat 1 Yohanes 4:8), sehingga Ia benci perceraian.
Beberapa orang Farisi pernah bertanya kepada Yesus tentang keabsahan perceraian “untuk alasan apapun.” JawabanNya menyatakan bahwa pada dasarnya Ia tidak setuju perceraian. Kenyataannya, Allah tak pernah menghendaki perceraian untuk siapapun:
Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?” Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Matius 19:3-6).
Menurut sejarah, ada dua kelompok pemikiran di antara para pemimpin agama Yahudi pada zaman Yesus. Kita selidiki dua kelompok pemikiran itu secara rinci, tetapi cukup dikatakan bahwa kelompok satu konservatif dan yang lain liberal. Kelompok konservatif percaya bahwa suami boleh menceraikan istrinya hanya karena alasan-alasan moral yang sangat serius. Kelompok liberal percaya bahwa suami boleh menceraikan istrinya karena alasan apapun, termasuk mendapatkan wanita yang lebih menarik. Pertentangan-pertentangan itu manjadi dasar pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus.
Yesus menunjuk pada ayat-ayat Alkitab dari bagian-bagian awal kitab Kejadian yang menunjukkan bagaimana rencana awal Allah untuk menyatukan pria dan wanita bersama untuk selamanya, bukan untul sementara. Musa menyatakan bahwa Allah menciptakan dua jenis kelamin, sambil memikirkan pernikahan keduanya; pernikahan adalah ikatan yang signifikan, yang menjadi ikatan yang utama. Ketika pernikahan diteguhkan, kedudukannya menjadi lebih tinggi dibandingkan hubungan seseorang dengan orangtua. Suami meninggalkan orang tuanya untuk menggantungkan diri kepada istrinya.
Lagipula, penyatuan seks antara suami dan istri menunjuk pada penyatuan yang Allah kehendaki. Jelas, Allah tidak menginginkan hubungan pernikahan sementara, yang menghasilkan keturunan. Saya ragu, ada nada kekecewaan yang dalam pada tanggapan Yesus terhadap orang-orang Farisi sampai pertanyaan itu dilontarkan. Allah sudah tentu tidak bermaksud agar suami menceraikan istrinya “karena alasan apapun.”
Allah pasti tidak ingin siapapun berbuat dosa dalam hal apapun, tetapi kita semua telah berdosa. Dengan penuh kasih, Allah mau menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Ia juga ingin mengatakan beberapa hal setelah kita melakukan apa yang tidak Ia inginkan. Dan, Allah tak pernah ingin siapapun untuk bercerai, tetapi perceraian tak dapat dihindarkan di antara manusia yang tidak berserah kepada Allah. Allah tidak terkejut pada perceraian pertama atau jutaan perceraian berikutnya. Sehingga Ia membenci perceraian dan juga Ia ingin mengatakan beberapa hal kepada mereka yang telah bercerai.
Pada Mulanya (In the Beginning)
Dengan peletakan dasar ini, kita dapat selidiki secara khusus pernyataan Allah tentang perceraian dan pernikahan kembali. Karena pernyataan-pernyataan paling kontroversial tentang perceraian dan pernikahan kembali menjadi bahan pembicaraan Yesus kepada orang-orang Israel, maka kita dapat mempelajari lebih dulu perkataan Allah tentang persoalan itu kepada orang-orang Israel ratusan tahun sebelumnya. Jika ditemukan ada pertentangan antara perkataan Allah melalui Musa dan perkataan Allah melalui Yesus, maka kita bisa yakin bahwa Hukum Taurat Allah telah berubah atau kita salah menafsirkan sesuatu dari perkataan Musa atau Yesus. Jadi, kita mulai dengan pengungkapan dari Allah mengenai perceraian dan pernikahan kembali.
Saya telah menyebutkan perikop itu dalam Kejadian 2 yang, menurut Yesus, memiliki relevansi dengan masalah perceraian. Kali ini, kita baca langsung dari kitab Kejadian:
Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. (Kejadian 2:22-24).
Itulah pernikahan pertama. Allah menciptakan wanita pertama dari manusia pertama dan untuk manusia pertama, dan Allah secara pribadi membawa perempuan itu kepada manusia itu. Dalam kata-kata Yesus, “Allah … telah mempersatukan [mereka]” (Matius 19:6, tambahkan penekanan). Pernikahan pertama yang ditentukan oleh Allah menjadi pola bagi pernikahan-pernikahan selanjutnya. Allah menciptakan jumlah wanita sama dengan jumlah pria, dan Ia ciptakan mereka sehingga satu jenis kelamin merasa tertarik kepada jenis kelamin lainnya. Maka dapat dikatakan, Allah masih menata pernikahan dalam skala besar (walau ada lebih banyak calon pasangan untuk seseorang dibandingkan untuk Adam dan Hawa). Karena itu, seperti yang Yesus tunjukkan, tak satupun manusia dapat memisahkan apa yang telah Allah persatukan. Allah tak ingin pasangan nikah hidup terpisah, tetapi mereka akan mendapat berkat dalam kebersamaan hidup dalam saling ketergantungan. Pelanggaran atas kehendak Allah akan menghasilkan dosa. Sehingga dari Kejadian pasal 2, perceraian bukanlah kehendak Allah dalam pernikahan.
Hukum Taurat Allah yang Dituliskan dalam Hati (God’s Law Written in Hearts)
Saya juga berpendapat bahwa orang yang belum pernah membaca Kejadian pasal 2 langsung tahu bahwa perceraian adalah keliru, karena janji pernikahan seumur hidup dilakukan di banyak budaya dari para penyembah berhala di mana mereka tak tahu tentang Alkitab. Sesuai tulisan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma:
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri . Sebab dengan itu mereka menunjukkan , bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. (Roma 2:14-15).
Kode etik Allah dituliskan di dalam hati setiap manusia. Ternyata, kode etik yang berbicara melalui kata hati menjadi aturan yang pernah Allah berikan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang Israel, sejak Adam sampai masa Yesus. Siapapun yang sedang berpikir untuk bercerai akan tahu bahwa ia harus memperhatikan kata-hatinya, dan cara untuk dapat mengatasi kata-hatinya adalah mencari pertimbangan yang baik untuk bercerai. Jika orang itu meneruskan proses perceraian tanpa pertimbangan yang baik, maka kata-hatinya akan menuduhnya, walaupun ia dapat menekan perasaan itu.
Sepanjang pengetahuan kita, selama duapuluh-tujuh generasi dari Adam sampai pemberian Hukum Taurat Musa kepada Israel sekitar tahun 1440 SM, hukum hati nurani adalah pewahyuan yang Allah berikan kepada setiap orang, termasuk orang-orang Israel, mengenai perceraian dan pernikahan kembali; Allah menganggapnya sudah cukup. (Ingat, Musa tidak menuliskan kisah penciptaan dalam Kejadian 2 sampai saat keluarnya bangsa Israel dari Mesir). Tentu, kita bisa berpendapat bahwa selama duapuluh-tujuh generasi sebelum Hukum Taurat Musa, termasuk zaman Air Bah Nuh, sebagian dari jutaan pernikahan selama ratusan tahun itu berakhir dengan perceraian. Kita bisa simpulkan bahwa Allah, yang tak pernah berubah, mau mengampuni orang yang menimbulkan rasa bersalah dari perceraian jika dia mengaku dan bertobat dari dosanya. Kita yakin bahwa orang dapat diselamatkan, atau dibenarkan oleh Allah melalui imannya, sebelum pemberian Hukum Taurat Musa, seperti halnya Abraham (lihat Roma 4:1-12). Jika orang-orang dapat dibenarkan melalui iman mereka dari Adam sampai Musa, itu berarti mereka dapat diampuni dari suatu hal, termasuk dosa yang timbul dari perceraian. Maka, saat kita mencari solusi untuk perceraian dan pernikahan kembali, saya ragu: Apakah orang-orang, yang menimbulkan dosa perceraian sebelum Hukum Taurat Musa dan yang menerima pengampunan dari Allah, dipersalahkan oleh kata-hatinya (karena tidak ada hukum tertulis) sehingga mereka menimbulkan rasa bersalah jika mereka menikah lagi? Saya hanya menuliskan pertanyaan ini.
Bagaimana dengan korban-korban perceraian yang tidak berbuat dosa, orang yang diceraikan tanpa kesalahannya, tetapi hanya karena pasangan hidup yang egois? Apakah kata-hati mereka mencegahnya untuk tak menikah lagi? Tampaknya tak mungkin. Jika suami meninggalkan istrinya untuk wanita lain, apa yang membuat istrinya berkesimpulan bahwa ia tak berhak menikah lagi? Wanita itu telah diceraikan tanpa berbuat salah.
Hukum Taurat Musa (The Law of Moses)
Belum sampai pada kitab ketiga dari Alkitab, kita dapati penyebutan secara spesifik tentang perceraian dan pernikahan kembali. Isi Hukum Taurat Musa adalah larangan terhadap imam-imam yang menikahi wanita-wanita yang diceraikan:
Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allah nya. (Imamat 21:7).
Di dalam Hukum Taurat Musa, tak ada larangan tersebut bagi kaum pria Israel. Dan, ayat di atas bermakna bahwa (1) sudah ada wanita-wanita Israel yang diceraikan, dan (2) tiada yang keliru dengan pria-pria Israel bukan imam yang menikah sebelumnnya. Hukum yang dikutip di atas hanya berlaku bagi imam dan wanita yang diceraikan yang mungkin menikahi imam. Dalam Hukum Taurat Musa, tiada yang keliru dengan pernikahan ulang dari wanita yang diceraikan, selama wanita itu tak menikahi imam. Selain imam, tak ada yang keliru bila pria manapun menikahi wanita yang diceraikan.
Imam kepala (mungkin sebagai tipe terbaik Kristus) harus hidup menurut standar yang lebih tinggi dibandingkan imam biasa. Ia bahkan tak boleh menikahi seorang janda. Kita baca beberapa ayat nanti dalam Imamat:
Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. (Imamat 21:14).
Apakah ayat itu membuktikan bahwa adalah dosa bila: (i) setiap dan semua janda Israel untuk menikah lagi, atau (ii) setiap dan semua pria Israel untuk menikahi janda? Tidak. Nyatanya, ayat itu bermakna bahwa janda manapun tidak berdosa bila menikahi pria manapun selama pria itu bukan imam kepala, dan ayat itu bermakna bahwa pria manapun, selain imam kepala, boleh menikahi janda. Ayat-ayat lain dalam Alkitab menegaskan legitimasi penuh dari janda yang menikah kembali (lihat Roma 7:2-3; 1 Tim.5:14).
Ayat di atas juga, juga dengan ayat sebelumnya (Imamat 21:7), bermakna bahwa bila pria Israel (selain imam atau imam kepala) boleh menikahi wanita yang diceraikan atau bahkan wanita yang tidak lagi perawan, “yang tercemar karena pelacuran.” Ayat ini juga bermakna bahwa, sesuai Hukum Taurat Musa, tak ada yang keliru bagi wanita yang diceraikan untuk menikah lagi atau bagi wanita “yang tercemar karena pelacuran” untuk menikah, selama ia tidak menikahi seorang imam. Allah dengan kasih karunianya memberi kesempatan kepada orang yang cabul dan orang yang bercerai, meskipun Ia sangat menentang percabulan dan perceraian.
Larangan Kedua terhadap Pernikahan Kembali (A Second Specific Prohibition Against Remarriage)
Berapa “kesempatan kedua” yang Allah berikan kepada wanita yang diceraikan? Dapatkah disimpulkan bahwa Allah memberikan kepada wanita yang diceraikan hanya satu kesempatan lagi menurut Hukum Taurat Musa, yang memungkinkan hanya satu pernikahan kembali? Ini kesimpulan keliru. Bacalah dalam Hukum Taurat Musa,
Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. (Ulangan 24:1-4).
Perlu dicatat, dalam ayat-ayat di atas, larangan dikenakan kepada wanita yang dua kali menikah (atau wanita yang pernah diceraikan dan pernah menjanda) yang menikahi kembali suami pertamanya. Tiada yang dapat dikatakan tentang rasa bersalahnya yang muncul karena menikah kedua kali, dan ketika ia diceraikan kali kedua (atau menjadi janda dari suami kedua), ia hanya dilarang kembali kepada suami pertama. Implikasi yang jelas adalah si wanita tadi bebas menikah lagi dengan pria manapun (yang mau mengambil kesempatan kepada wanita itu). Andaikata dia berdosa karena menikah kembali dengan pria lain, maka Allah tak mungkin perlu memberi instruksi khusus seperti itu. Yang dapat dikatakan adalah, “Orang yang diceraikan dilarang menikah kembali.”
Lagipula, jika Allah izinkan wanita itu menikah kedua kali, maka pria yang menikah dengannya, setelah perceraian pertama si wanita, tidak menimbulkan rasa bersalah. Dan jika si wanita diizinkan menikah ketiga kali, maka pria manapun, yang menikahinya setelah si wanita bercerai dua kali, tidak berdosa (jika ia tidak menjadi suaminya yang pertama). Jadi, Allah yang membenci perceraian mengasihi orang yang diceraikan, dan Ia dengan penuh kasih memberikan mereka kesempatan lain.
Ikhtisar (A Summary)
Kita buat kesimpulan dari hal-hal yang telah didapatkan: Meskipun Allah mengatakan kebencianNya atas perceraian, Ia tak memberikan indikasi sebelum atau selama perjanjian lama bahwa pernikahan kembali adalah dosa, dengan dua pengecualian: (1) wanita, yang dua kali diceraikan atau yang sekali diceraikan dan sekali menjanda, yang menikahi kembali suami pertama, dan (2) perkara wanita yang diceraikan yang menikahi seorang imam. Lagipula, Allah tidak memberi indikasi bahwa menikahi seorang yang diceraikan adalah dosa bagi siapapun, kecuali bila dilakukan oleh imam.
Hal itu bertentangan dengan ucapan Yesus tentang orang yang diceraikan yang menikah kembali dan orang yang menikahi orang yang diceraikan. Yesus berkata bahwa orang-orang itu berzinah (lihat Matius 5:32). Jadi, kita salah-paham kepada Yesus atau Musa, atau Allah mengubah Hukum TauratNya. Saya curiga, kita bisa salah tafsir dengan ajaran Yesus, karena tampak aneh bila Allah tiba-tiba menyatakan sesuatu sebagai berdosa menurut moral yang diberlakukan selama seribu limaratus tahun dalam Hukum Taurat yang Dia berikan kepada Israel.
Sebelum kita atasi kontradiksi itu dengan jelas, saya ingin tekankan bahwa persetujuan dari Allah untuk menikah kembali menurut perjanjian lama tidak memberikan ketentuan yang berdasarkan alasan perceraian seseorang atau kadar rasa bersalah yang ditimbulkan oleh seseorang dalam perceraian. Allah tak pernah berkata bahwa orang yang diceraikan tidak memenuhi syarat untuk menikah kembali karena perceraiannya bukan karena alasan sah. Allah tidak berkata bahwa sebagian orang boleh menikah kembali oleh karena keabsahan perceraian itu. Namun penilaian sering dibuat oleh pelayan kini berdasarkan kesaksian sepihak. Misalnya, istri yang diceraikan mencoba meyakinkan pendetanya bahwa ia diizinkan menikah kembali karena ia menjadi korban perceraian. Mantan suaminya menceraikannya —ia tidak menceraikan suaminya. Tetapi, jika pendeta diberi kesempatan mendengarkan cerita dari bekas suaminya, ia bisa saja bersimpati kepada mantan suaminya. Mungkin istrinya galak dan layak disalahkan.
Saya mengenal seorang suami dan istri yang melakukan provokasi untuk bercerai agar masing-masing dapat menghindari rasa bersalah karena ikut bercerai. Keduanya ingin mengatakan setelah perceraian bahwa pasangannyalah, bukan mereka berdua, yang mau bercerai, sehingga tindakan itu memberi pengesahan bagi masing-masing untuk menikah kedua kali. Kita bisa saja membodohi orang lain, tetapi kita tak dapat membodohi Allah. Misalnya, apa penghargaanNya bagi wanita yang, dalam ketidaktaatan pada Firman Tuhan, terus menolak hubungan seks dengan suaminya, lalu menceraikannya karena ia tak setia kepada istrinya? Apakah istri tak sedikitpun bertanggung-jawab atas perceraian?
Kasus wanita yang dua kali diceraikan dalam Ulangan 24 tidak menyatakan tentang legitimasi kedua perceraiannya. Suami pertamanya mendapati ”ketidaksenonohan” pada wanita itu. Jika ”ketidaksenonohan” itu adalah perzinahan, maka wanita itu layak dihukum mati menurut Hukum Taurat Musa, yang menganjurkan bahwa pezinah harus dilempari batu (lihat Imamat 20:10). Jadi, jika perzinahan menjadi alasan bercerai, mungkin suami pertamanya tidak punya alasan tepat untuk menceraikannya. Di lain pihak, mungkin si wanita telah berzinah, dan si suami, bagaikan orang benar seperti Yusuf suami Maria, “bermaksud menceraikannya dengan diam-diam” (Matius 1:19). Mungkin ada banyak skenario.
Suami keduanya konon telah “berbalik melawannya.” Sekali lagi, kita tidak tahu siapa yang patut disalahkan atau apakah mereka menanggung kesalahan bersama-sama. Tetapi hal itu takkan memberi perbedaan apapun. Kasih karunia Allah diberikan kepada istri untuk menikah kembali dengan siapapun yang mengambil kesempatan kepada wanita yang dua kali bercerai, kecuali suami pertamanya.
Keberatan (An Objection)
Sering muncul keluhan “Tetapi jika orang tahu bahwa ia boleh menikah kembali setelah bercerai dengan suatu alasan, yang akan mendorongnya untuk bercerai karena alasan yang tidak sah.” Saya berpendapat mungkin saja hal itu berlaku pada kasus orang yang taat yang tidak berusaha untuk menyenangkan Allah, tetapi agaknya tak ada gunanya mencegah orang yang tidak berserah kepadaNya agar tak berbuat dosa. Namun, setiap orang yang mau berserah kepada Allah di dalam hatinya tak akan berniat untuk berbuat dosa. Orang itu mencoba menyenangkan Allah, dan orang seperti itu biasanya punya ikatan pernikahan kuat. Lagipula, pada masa perjanjian lama sepertinya Allah tak peduli kepada orang-orang yang bercerai karena alasan yang tidak sah yang disebabkan oleh aturan terbuka bagi pernikahan kembali, sebab Allah memberi aturan terbuka itu kepada orang-orang Israel.
Apakah kita tak perlu berkata kepada orang yang dosanya Allah mau ampuni, agar ia tak terdorong untuk berbuat dosa karena ia tahu ada pengampunan? Jika demikian, kita akan berhenti memberitakan Injil. Lagi-lagi, hal tersebut berpangkal pada kondisi hati setiap orang. Orang yang mengasihi Allah mau menaatiNya. Saya tahu, pengampunan Allah ada bagi saya jika saya memintanya, tak peduli dosa apa yang saya buat. Tetapi hal itu sama sekali tidak memotivasi saya untuk berbuat dosa, karena saya mengasihi Allah dan telah dilahirkan kembali. Saya telah diubahkan oleh kasih karuniaNya. Dan, saya mau menyenangkanNya.
Bagai Allah, tak perlu lagi menambah konsekwensi negatif kepada banyak konsekwensi negatif dalam perceraian yang tak terhindarkan demi memotivasi setiap pasangan nikah untuk tetap dalam ikatan pernikahan. Upaya yang sedikit memberi motivasi agar tetap dalam ikatan pernikahan adalah mengatakan kepada orang yang pernikahannya bermasalah agar ia lebih baik tak bercerai karena ia tak boleh menikah lagi. Walau orang itu mempercayai anda, hidup sendirian sepertinya menjanjikan kebahagiaan kepada orang itu, dibandingkan hidup dalam pernikahan yang terus dirundung malang.
Paulus tentang Pernikahan Kembali (Paul on Remmariage)
Sebelum kita bahas tentang kesesuaian perkataan Yesus dengan Musa dalam hal pernikahan kembali, kita perlu tahu ada seorang dalam Alkitab yang sependapat dengan Musa; ia adalah rasul Paulus. Paulus menuliskan bahwa pernikahan kembali untuk orang-orang yang bercerai adalah dosa, dan ia sepakat dengan perkataan Perjanjian Lama:
Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat, bahwa, mengingat waktu darurat sekarang, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang! Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. (1 Korintus 7:25-28, tambahkan penekanan).
Dalam perikop itu, nyata-nyata Paulus menunjuk kepada orang yang diceraikan. Ia menyarankan kepada orang yang kawin, orang yang tak pernah kawin, dan orang yang bercerai agar tetap dalam keadaannya seperti itu oleh karena penganiayaan yang diderita oleh orang-orang Kristen saat itu. Tetapi, Paulus jelas meminta agar orang yang diceraikan dan anak gadis tidak melakukan dosa jika mereka menikah.
Perlu dicatat bahwa Paulus tidak membatasi keabsahan pernikahan kembali dari orang yang bercerai. Ia tidak mengatakan pernikahan kembali hanya diizinkan jika orang-orang yang bercerai tidak mau disalahkan pada perceraiannya terdahulu. (Dan siapakah yang memenuhi syarat untuk menghakimi hal seperti itu, selain Allah?). Ia tidak mengatakan pernikahan kembali hanya boleh bagi mereka yang telah bercerai sebelum ia diselamatkan. Ia hanya berkata bahwa pernikahan kembali bukanlah dosa bagi orang yang diceraikan.
Apakah Paulus Bersikap Lunak terhadap Perceraian? (Was Paul Soft on Divorce?)
Karena Paulus mendukung kebijakan yang penuh kasih-karunia terhadap pernikahan kembali, apakah itu berarti ia juga bersikap lunak terhadap perceraian? Tidak, secara umum Paulus jelas menentang tindakan perceraian. Pada awal pasal yang sama dari surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, ia menerapkan aturan perceraian yang sesuai dengan sikap benci Allah terhadap perceraian:
Kepada orang-orang yang telah kawin aku–tidak, bukan aku, tetapi Tuhan–perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu? Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. (1 Korintus 7:10-17).
Perlu dicatat, mula-mula Paulus berbicara kepada orang percaya yang menikah dengan orang percaya. Sudah tentu, mereka tidak boleh bercerai, dan Paulus menyatakan bahwa itulah perintah Tuhan, bukan perintahnya. Dan tentunya, hal itu selaras dengan segala sesuatu yang kita bahas dalam Alkitab sejauh ini.
Di sinilah hal itu jadi menarik. Paulus bersikap cukup realistis untuk menyadari bahwa kadang-kadang orang-orang percaya bisa bercerai. Jika hal itu terjadi, Paulus menyatakan bahwa orang yang menceraikan pasangannya harus tetap tidak menikah atau rujuk kembali dengan pasangannya. (Walaupun Paulus memberi perintah khusus itu kepada istri, saya anggap bahwa aturan yang sama berlaku juga bagi suami).
Tulisan Paulus tidak mengejutkan kita. Awalnya, Ia menegaskan peraturan Allah mengenai perceraian, tetapi ia cukup tahu bahwa peraturan Allah tidak selalu ditaati. Jadi ketika dosa perceraian terjadi antara dua orang percaya, ia memberi instruksi lanjutan. Orang yang menceraikan pasangannya harus tetap tidak menikah atau didamaikan dengan pasangannya. Hal itu adalah tindakan terbaik bagai perceraian antara orang-orang percaya. Selama mereka berdua tetap tidak menikah lagi, ada harapan untuk rujuk kembali, dan itulah jalan terbaik. Tentu saja, jika salah seorang menikah lagi, maka berakhirlah harapan dan kemungkinan rujuk kembali. (Dan jelas, jika mereka telah melakukan hal yang tak dapat diampuni melalui perceraian, ada alasan yang diberikan Paulus kepada mereka untuk tetap tidak menikah lagi atau didamaikan kembali).
Apakah anda berpendapat bahwa Paulus tahu bahwa petunjuknya yang kedua kepada orang percaya yang bercerai mungkin tidak selalu ditaati? Saya sependapat. Mungkin ia tidak memberi petunjuk lanjutan kepada orang percaya yang bercerai karena ia berharap agar orang percaya sejati mengikuti petunjuknya untuk tak bercerai, sehingga petunjuknya yang kedua diperlukan hanya untuk kasus yang jarang terjadi. Tentu saja, pengikut sejati Kristus, jika dapat masalah pernikahan, akan berbuat apa saja untuk menjaga pernikahan. Dan tentunya seorang percaya yang, setelah coba mempertahankan pernikahan, merasa tak punya pilihan kecuali bercerai, tentunya orang percaya itu, dari perasaan malu dan keinginannya untuk menghormati Kristus, tidak berpikir untuk menikah kembali dengan siapapun, dan masih berharap rujuk kembali. Bagiku, masalah sebenarnya dalam gereja masa kini dalam hal perceraian adalah banyak orang percaya yang sedang tersesat, orang-orang yang tak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan berserah kepadaNya.
Dari tulisan Paulus dalam 1 Korintus 7, jelaslah Allah sangat berharap bagi orang-orang percaya, di mana Roh Kudus berdiam di dalam diri mereka, dibandingkan yang Dia lakukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Seperti kita baca, Paulus menuliskan bahwa orang percaya tak boleh menceraikan pasangannya yang tak percaya selama pasangannya itu bersedia tinggal bersama. Sekali lagi, petunjuk itu tidak mengejutkan, karena sesuai sekali dengan semua yang terdapat dalam Alkitab, terkait dengan pokok masalahnya. Allah menentang perceraian. Tetapi, Paulus berkata lagi bahwa jika orang yang tidak percaya ingin bercerai, maka Paulus membolehkannya. Paulus tahu bahwa orang yang tidak percaya tidak berserah kepada Allah, dan ia tidak mengharapkan orang yang tidak percaya untuk bertindak seperti orang percaya. Dapat saya tambahkan, ketika orang yang tidak percaya setuju untuk hidup bersama dengan orang percaya, maka ada indikasi baik bahwa orang yang tidak percaya berpeluang membuka diri terhadap Injil, atau orang percaya itu berbalik menjadi tidak percaya atau orang Kristen palsu.
Kini, siapa yang akan berkata bahwa orang percaya yang telah diceraikan oleh seorang tak percaya tidak bebas untuk menikah kembali? Paulus tidak mengatakan hal tersebut, seperti yang ia lakukan dalam kasus dua orang percaya yang diceraikan. Kita heran mengapa Allah menentang pernikahan kembali orang percaya yang telah diceraikan oleh seorang yang tidak percaya. Apa tujuannya? Namun tampaknya pemberian izin itu bertentangan dengan ucapan Yesus tentang pernikahan kembali: “Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.” (Matius 5:32). Hal tersebut membuat saya curiga bahwa kita salah menafsirkan penyampaian dari Yesus.
Masalah (The Problem)
Yesus, Musa dan Paulus sependapat bahwa perceraian adalah indikasi dosa dari satu pihak atau dua pihak yang bercerai. Pada umumnya, ketiganya konsisten menentang perceraian. Tetapi, masalahnya: Bagaimana kita mencocokkan apa yang dikatakan oleh Musa dan Paulus tentang pernikahan kembali dengan perkataan Yesus tentang pernikahan kembali? Kita tentu berharap ketiganya memiliki pendapat yang selaras karena semuanya diilhami oleh Allah untuk menyatakan perkataan mereka.
Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?” Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Kata mereka kepada-Nya: “Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” (Matius 19:3-9).
Selama percakapan dengan Yesus, orang-orang Farisi menyebutkan bagian dari Hukum Taurat yang disebut sebelumnya, Ulangan 24:1-4. Tertulis, “Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya…” (Ulangan 24:1, tambahkan penekanan).
Pada masa Yesus, sudah ada dua kelompok pemikiran mengenai hal yang merupakan “ketidaksenonohan.” Sekitar duapuluh tahun sebelumnya, seorang rabbi bernama Hillel mengajarkan bahwa ketidaksenonohan adalah perbedaan yang bertentangan. Sebelum Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi, penafsiran “Hillel” bahkan menjadi lebih liberal, yang membolehkan perceraian karena “alasan apa saja”, sebagaimana tampak pada pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Suami dapat saja menceraikan istrinya jika ia membuat masakan hangus, memberi terlalu banyak garam pada makanan, berjalan-jalan di muka umum sehingga lututnya terbuka, memotong rambutnya, berbicara kepada pria lain, berkata sesuatu yang tak baik tentang ibu mertuanya, atau bila ia mandul. Seorang suami dapat menceraikan istrinya jika ia melihat seseorang yang lebih menarik, sehingga menjadikan istrinya “tidak menarik.”
Rabbi lain yang terkenal, Shammai, yang hidup sebelum Hillel, mengajarkan bahwa “ketidaksenonohan” adalah sesuatu yang sangat tak bermoral, seperti perzinahan. Agak diragukan, di antara orang-orang Farisi di zaman Yesus, penafsiran liberal Hillel jauh lebih dikenal dibandingkan penafsiran Shammai. Orang-orang Farisi hidup dan mengajarkan bahwa perceraian adalah sah dalam hal apapun, sehingga perceraian tak terelakkan. Dalam cara menurut tradisi Farisi, orang-orang Farisi mengutamakan pentingnya pemberian surat cerai ketika menceraikan istrinya, agar “tidak melanggar Hukum Taurat Musa.”
Jangan Lupa bahwa Yesus Berbicara kepada Orang-orang Farisi (Don’t Forget that Jesus’ was Speaking to Pharisees)
Dengan mengingat latar-belakang itu, kita makin mengerti keadaan yang Yesus hadapi. Di depanNya berdiri para guru agama munafik yang, kebanyakan atau mungkin semua, telah bercerai sekali atau lebih, dan mungkin karena mereka telah temukan pasangan yang lebih menarik. (Menurut saya, bukan kebetulan bahwa perkataan Yesus tentang perceraian dalam Khotbah di Bukit secara langung mengikuti semua peringatanNya mengenai hawa-nafsu, yang juga menyebutnya sebagai bentuk perzinahan). Namun mereka membenarkan diri mereka sendiri, dengan mengklaim telah menaati Hukum Taurat Musa.
Pertanyaan mereka sendiri mengungkapkan kecenderungan mereka. Mereka percaya bahwa orang bisa saja menceraikan istrinya karena alasan apapun. Yesus mengungkapkan kekeliruan pemahaman mereka akan maksud Allah dalam pernikahan dengan merujuk pada kata-kata Musa tentang pernikahan pada Kejadian pasal 2. Allah tak pernah ingin terjadi perceraian apapun, “dengan alasan apapun”, namun para pemimpin Israel menceraikan istri-istri mereka persis seperti remaja mengakhiri “kebiasaan” mereka!
Saya curiga orang-orang Farisi sudah tahu pendirian Yesus tentang perceraian, ketika Ia menyatakan di depan banyak orang sebelumnya, sehingga mereka sudah siap membuat penyangkalan: “… apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” (Matius 19:7).
Pertanyaan itu kembali mengungkapkan kecurigaan mereka. Pertanyaan itu dibuat sehingga berbunyi seolah-olah Musa memerintakan suami untuk menceraikan istri ketika ia menemukan “ketidaksenonohan,” dan memerlukan surat cerai, tetapi seperti dalam Ulangan 24:1-4, itu bukanlah perkataan Musa. Ia hanya memberi aturan untuk pernikahan ketiga oleh seorang wanita, dengan melarangnya untuk menikahi lagi suami pertamanya.
Karena Musa menyebut perceraian, pasti perceraian dibolehkan dengan satu alasan. Tetapi, perhatikan bagaimana kata yang Yesus pakai dalam jawabanNya, membolehkan, berbeda dengan pilihan kata dari orang-orang Farisi: memerintahkan. Musa membolehkan, tetapi tak pernah memerintahkan, perceraian. Musa membolehkan perceraian karena kekerasan hati bangsa Israel. Yakni, Allah membolehkan perceraian sebagai persetujuan dengan kasih karunia kepada keadaan berdosa manusia. Ia tahu seseorang tak akan setia kepada pasangannya. Ia tahu akan terjadi kejatuhan moral. Ia tahu hati orang yang disakiti. Sehingga Ia membolehkan perceraian. Bukan itu yang saya maksudkan dari awal, tetapi dosa membuat perceraian perlu dilakukan.
Berikutnya, Yesus menerapkan aturan Allah kepada orang-orang Farisi, dengan mendefiniskan kata “ketidaksenonohan” dari Musa: “Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.” ” (Matius 19:9, tambahkan penekanan). Di mata Allah, zinah adalah satu-satunya alasan sah bagi suami untuk menceraikan istrinya, dan saya pahami itu. Apa yang bisa dilakukan oleh pria atau wanita yang bisa saja menjadi tindakan yang tak menyenangkan pasangannya? Ketika berzinah atau berselingkuh, si pria/wanita mengirimkan pesan yang jahat. Yesus tentu tak menyebut perzinahan ketika memakai kata “amoralitas.” Tentunya mencium dan mencumbu pasangan dengan bernafsu merupakan penyimpangan amoral, seperti halnya melihat-lihat gambar porno, dan penyimpangan seks lainnya. Ingatlah, Yesus menyamakan nafsu dengan perzinahan selama KhotbahNya di Bukit.
Jangan lupa, kepada siapa Yesus berbicara, yakni kepada orang-orang Farisi yang menceraikan istri-istri mereka dengan alasan apapun dan dengan cepat menikah kembali, tetapi mereka tidak melakukan zinah, seperti yang dilarang Allah, demi berjaga agar mereka tidak melanggar perintah ketujuh. Yesus berkata bahwa mereka hanya membodohi diri. Perilaku mereka tak berbeda dengan perzinahan. Orang jujur paham bahwa seseorang, yang menceraikan istrinya agar dapat menikahi wanita lain, tengah berbuat zinah, tetapi bersembunyi di balik legalitas.
Solusi (The Solution)
Inilah kunci untuk menyelaraskan Yesus dengan Musa dan Paulus. Yesus memaparkan kemunafikan orang-orang Farisi. Ia tidak menetapkan peraturan yang melarang pernikahan kembali. Jika Ia menetapakan peraturan, maka Ia menentang pendapat Musa dan Paulus dan membingungkan jutaan orang yang bercerai dan jutaan orang yang menikah ulang. Jika, Yesus menetapkan aturan nikah kembali, maka apa yang harus dikatakan kepada orang yang telah diceraikan dan menikah kembali sebelum ia mendengar tentang peraturan Yesus? Apakah kita harus berkata bahwa ia sedang hidup dalam zinah dan menganjurkan dia untuk bercerai lagi, karena Alkitab ingatkan bahwa tak ada pezinah akan mewarisi Kerajaan Allah (lihat 1 Korintus 6:9-10)? Tetapi tidakkah Allah membenci perceraian?
Apakah kita harus berkata kepadanya untuk berhenti berhubungan seks dengan pasangannya sampai mantan pasangannya meninggal untuk menghindari perzinahan? Tetapi tidakkah Paulus melarang pasangan yang sudah menikah untuk saling menolak hubungan seks? Tidakkah saran itu menimbulkan godaan seks dan bahkan memicu keinginan bekas pasangan untuk mati?
Apakah kita harus berkata kepada orang itu untuk menceraikan pasangannya kini dan menikahi pasangan aslinya (seperti anjuran sebagian orang), sesuatu yang dilarang dalam Hukum Taurat Musa dalam Ulangan 24:1-4?
Bagaimana dengan orang yang diceraikan yang tidak kawin lagi? Jika ia hanya boleh menikah kembali jika bekas pasangannya melakukan amoralitas, yang akan bertanggung jawab untuk menentukan apakah amoralitas memang dilakukan? Untuk menikah kembali, apakah seseorang perlu membuktikan bahwa bekas pasangannya bersalah hanya karena hawa-nafsu, sedangkan orang lain perlu membawa saksi bagi perselingkuhan yang dilakukan oleh bekas pasangan tadi?
Seperti pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana halnya dengan bekas pasangan yang berzinah karena dinikahi oleh seseorang yang tak mau berhubungan seks? Adilkah bila orang yang tak mau berhubungan seks dibolehkan menikah kembali selagi orang yang berzinah tidak diizinkan untuk kawin lagi?
Bagaimana dengan orang yang telah bersetubuh sebelum nikah? Bukankah perbuatan itu wujud ketidaksetiaaan kepada calon pasangan nanti? Tidakkah dosa orang itu sama dengan perzinahan, andaikan ia atau pasangan seksnya sudah menikah ketika berbuat dosa? Lalu, mengapa orang itu dibolehkan menikah?
Bagaimana dengan dua orang yang hidup bersama, tanpa ikatan pernikahan, yang kemudian “berpisah.” Mengapa mereka boleh menikahi orang lain setelah berpisah, hanya karena mereka tidak menikah resmi? Bagaimana mereka berbeda dengan orang-orang yang bercerai dan menikah kembali?
Bagaimana dengan fakta bahwa “yang lama sudah berlalu” dan “yang baru sudah datang” ketika seseorang menjadi pengikut Kristus (lihat 2 Korintus 5:17)? Apakah itu berarti setiap dosa yang dilakukan kecuali dosa perceraian yang tidak sah?
Semua itu dan lebih banyak pertanyaan
[1]
dapat dilontarkan, yang menjadi alasan kuat untuk berpendapat bahwa Yesus tak menetapkan aturan baru tentang pernikahan kembali. Tentu saja Yesus tahu konsekwensi dari aturan baruNya tentang pernikahan kembali jika sudah demikian adanya seperti sebelumnya. Cukup kita tahu bahwa Yesus hendak mengungkap kemunafikan orang-orang Farisi —orang-orang yang bernafsu, beragama dan munafik yang menceraikan istri dengan “alasan apapun” dan yang menikah kembali.
Tentu saja alasan, yang Yesus katakan bahwa mereka “berzinah” bukannya berkata bahwa yang perilaku mereka adalah keliru, adalah karena Ia ingin mereka sadari bahwa perceraian dengan alasan apapun dan pernikahan kembali tak berbeda dengan perzinahan, hal yang tak pernah mereka lakukan. Apakah kita akan simpulkan bahwa kepedulian Yesus adalah aspek seksual dari pernikahan kembali; dan apakah kita akan simpulkan bahwa Ia menyetujui pernikahan kembali selama ada penolakan hubungan seks? Jelas tidak. Jadi, kita tak perlu memintaNya untuk mengatakan hal yang tidak Ia kehendaki.
Perbandingan yang Bijaksana (A Thoughtful Comparison)
Bayangkan ada dua pria. Pria pertama sudah menikah, taat beribadah, yang menyatakan mengasihi Allah dengan seluruh hatinya, dan yang mulai tergila-gila kepada gadis muda tetangga. Ia segera menceraikan istrinya, lalu menikahi gadis itu.
Pria kedua tidak beribadah. Ia tak pernah mendengar Injil dan hidup dengan gaya hidup penuh dosa, yang akhirnya membuat dia harus menikah. Beberapa tahun kemudian, sebagai bujangan, ia mendengar Injil, bertobat, dan mulai mengikuti Yesus dengan sepenuh hatinya. Tiga tahun kemudian ia mencintai seorang wanita Kristen yang sangat berkomitmen yang ia temui di gereja. Mereka berdua setia mencari Tuhan dan melakukan konseling bersama, lalu menikah. Mereka menikah, dan melayani Tuhan dan saling melayani dengan setia sampai mati.
Kini, kita asumsikan kedua pria itu berbuat dosa dengan melakukan pernikahan ulang. Siapakah yang memiliki dosa yang lebih besar? Jelas, si pria pertama. Ia bagaikan pezinah.
Tetapi bagaimana si pria kedua? Apakah benar-benar ia telah berbuat dosa? Apakah ia tak berbeda dengan pezinah, seperti dikatakan kepada orang pertama? Saya tidak yakin. Haruskah kita berkata padanya perkataan Yesus tentang orang yang bercerai dan menikah kembali, dengan memberitahukan bahwa ia kini hidup dengan wanita yang bukan jodoh dari Allah, karena Allah menganggapnya masih menikah dengan istri pertamanya? Haruskah kita berkata padanya bahwa ia hidup dalam perzinahan?
Jawabannya jelas. Perzinahan dilakukan oleh orang yang telah menikah yang memandangi orang selain pasangannya. Jadi, menceraikan pasangan karena bertemu dengan orang yang lebih menarik sama dengan perzinahan. Tetapi orang yang belum kawin tak dapat berzinah karena ia tidak punya pasangan yang tidak setia, dan orang yang diceraikan tidak dapat berzinah karena ia tidak punya pasangan yang bisa ia khianati. Ketika kita pahami konteks Alkitab dan sejarah perkataan Yesus, kita tidak mendapat kesimpulan yang tak masuk akal dan yang bertentangan dengan Alkitab.
Sementara itu, ketika murid-murid mendengar jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi, mereka menanggapi, “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin” (Matius 19:10). Ketahuilah, mereka telah bertumbuh dengan pengajaran dan pengaruh orang-orang Farisi, dan dalam budaya yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang Farisi. Mereka tak pernah pikir bahwa pernikahan harus begitu lama. Nyatanya, beberapa menit sebelumnya, mereka juga mungkin percaya bahwa seseorang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Sehingga mereka cepat menyimpulkan bahwa sebaiknya menghindari pernikahan bersama-sama, sehingga tidak beresiko untuk melakukan perceraian dan perzinahan.
Yesus menjawab,
Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. (Matius 19:11-12).
Yakni, dorongan seks seseorang dan/atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan itu lebih merupakan faktor penentu. Bahkan Paulus berkata, “Sebab lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu.” (1 Korintus 7:9). Orang yang lahir tidak menikah atau yang dijadikan tak bisa menikah oleh pria (seperti dilakukan oleh pria yang membutuhkan pria lain yang dipercayakan untuk menjaga haremnya) tak punya dorongan seks. Orang yang menjadikan “dirinya sendiri tak bisa menikah demi kerajaan sorga” tampak menjadi orang yang diberi karunia khusus oleh Allah dengan pengendalian diri ekstra, yang menjadi alasan “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja” (Matius 19:11).
Khotbah di Bukit (The Sermon on the Mount)
Kita harus ingat bahwa selama KhotbahNya di Bukit, Yesus berbicara kepada banyak orang yang juga orang-orang yang hidupnya dipengaruhI oleh orang-orang Farisi, para penguasa dan guru bermuka dua di Israel. Saat kita pelajari dalam pelajaran awal kita tentang Khotbah di Bukit, jelaslah bahwa banyak perkataan Yesus tidak lebih sebagai koreksi dari ajaran sesat dari orang-orang Farisi. Yesus bahkan berkata kepada orang banyak bahwa mereka tidak akan masuk ke Kerajaan Sorga jika hidup keagamaan mereka tidak lebih benar dari hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi (lihat Matius 5:20); ungkapan ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan masuk neraka. Di akhir khotbahNya, orang banyak terkejut sebagian karena Yesus mengajar “tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka” (Matius 7:29).
Pada awal khotbahNya, Yesus mengungkapan kemunafikan mereka yang mengaku tak pernah berzinah, tetapi yang berhawa-nafsu atau yang bercerai dan menikah kembali. Ia memperluas arti perzinahan selain tindakan dosa secara fisik antara dua orang yang sudah menikah. PerkataanNya jelas bagi tiap orang jujur yang baru saja memikirkan hal itu. Ingat, sampai saat Yesus berkhotbah, sebagian besar orang dalam rombongan berpikir bahwa bercerai dengan “alasan apapun” dibolehkan. Yesus inginkan para pengikutNya dan siapapun tahu bahwa maksud Allah dari mulanya adalah standar yang jauh lebih tinggi.
Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. (Matius 5:27-32).
Mula-mula, seperti saya sebutkan sebelumnya, perhatikan perkataan Yesus tentang perceraian dan pernikahan kembali yang tidak hanya secara langsung mengikuti FirmanNya tentang hawa-nafsu, dengan mengaitkan kedua hal itu, tetapi juga Yesus menyamakan kedua hal tersebut sebagai perzinahan. Sehingga kita lihat jalinan yang menelusuri seluruh bagian itu dalam Alkitab. Yesus membantu para pengikutNya untuk memahami hal yang menyertai tindakan penaatan perintah ketujuh. Penaatan perintah itu juga berarti tidak mengumbar hawa-nafsu, tidak bercerai dan tidak menikah kembali.
Setiap orang dalam rombongan orang Yahudi di zamanNya sudah tahu perintah ketujuh yang dibaca di sinagoga (tak seorangpun punya Alkitab), dan mereka mendengar pemaparan juga menyaksikan aplikasinya dalam kehidupan para guru, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus lalu berkata, “tetapi Aku berkata kepada kalian”, tetapi Ia tidak menambahkan hukum-hukum baru. Ia hanya mengungkap maksud sebenarnya dari Allah.
Pertama, hawa-nafsu dilarang oleh perintah kesepuluh, dan bahkan tanpa perintah kesepuluh, siapapun yang memikirkan hawa-nafsu sadar bahwa mengingini hal yang Allah benci adalah keliru.
Kedua, dari pasal-pasal awal kitab Kejadian, Allah memperjelas bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Lagipula, siapapun yang memikirkan pernikahan akan berkesimpulan bahwa perceraian dan pernikahan kembali adalah perzinahan, terutama ketika seseorang bercerai untuk menikah kembali.
Tetapi dalam khotbah itu, sudah jelas Yesus hanya ingin menolong orang untuk memahami kebenaran tentang hawa-nafsu dan kebenaran tentang perceraian untuk alasan apapun dan pernikahan kembali. Ia tidak menetapkan hukum baru untuk pernikahan kembali yang sampai kini tidak “ada dalam kitab-kitab.”
Hal yang menarik adalah sedikit sekali orang dalam gereja yang pernah menafsirkan perkataan Yesus tentang mencungkil matanya atau memotong tangannya dalam arti sebenarnya, karena ide-ide itu muncul demikian yang bertentangan dengan bagian lain dalam Alkitab, dan ide-ide itu hanya menjadi dasar kuat untuk menghindari godaan seks. Namun, banyak orang di gereja berusaha menafsirkan perkataan Yesus dengan arti kata sebenarnya tentang orang yang menikah kembali yang melakukan zinah, bahkan ketika penafsiran itu bertentangan dengan Alkitab. Yesus bermaksud agar para pendengarNya menghadapi kebenaran, agar tidak banyak terjadi perceraian. Jika para pengikutNya menyimpan perkataanNya di dalam hati tentang hawa-nafsu, tidak akan ada amoralitas di antara mereka. Jika tak ada amoralitas, tak akan ada dasar sah bagi perceraian, dan tak akan ada perceraian, sesuai maksud Allah dari awal.
Bagaimana Suami Membuat Istrinya Berzinah? (How Does a Man Make His Wife Commit Adultery?)
Perhatikan ucapan Yesus, “Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah.” Ini membuat kita percaya bahwa Ia tidak memberikan aturan baru tentang pernikahan kembali, tetapi hanya mengungkapkan kebenaran tentang dosa suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang baik. Ia “menjadikan istrinya berzinah.” Jadi, sebagian orang berkata bahwa Yesus melarang istrinya menikah kembali, karena Ia menyebutnya sebagai perzinahan. Tetapi itu aneh. Penekanan ada pada dosa suami yang melakukan perceraian. Karena hal yang suami lakukan, istrinya tak punya pilihan lain kecuali menikah kembali, yang bukan jadi dosa baginya ketika ia menjadi korban keegoisan suaminya. Tetapi, di mata Allah, karena suami meninggalkan istrinya dalam keadaan tak punya apa-apa dan tanpa pilihan lain kecuali menikah kembali, seolah-olah ia memaksa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Jadi, orang yang menganggap suami belum berzinah dianggap bersalah karena perzinahan ganda, perzinahannya sendiri dan perzinahan istrinya.
Yesus tidak berkata bahwa Allah menganggap istri yang jadi korban sebagai bersalah karena zinah, karena hal itu tidak adil, dan nyatanya hal itu tak berarti bila istri yang jadi korban itu tak pernah kawin lagi. Bagaimana dapat Allah berkata bahwa ia berzinah jika ia tak menikah lagi? Bagaimanapun juga, hal itu tak masuk akal. Jelaslah, Allah menganggap suami bersalah karena perzinahannya, dan “perzinahan” istrinya, yang ternyata bukan perzinahan sama sekali bagi istrinya. Itulah pernikahan kembali yang sesuai aturan.
Dan bagaimana pernyataan Yesus bahwa “siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”? Hanya ada dua kemungkinan logis. Apakah Yesus menambahkan cuplikan ketiga tentang perzinahan terhadap pria yang beranggapan bahwa ia tak pernah berzinah (untuk alasan serupa seperti Ia menambahkan cuplikan kedua), atau Yesus sedang berbicara tentang pria yang mendesak seorang wanita untuk menceraikan suaminya demi menikahinya agar “tidak melakukan perzinahan.” Jika Yesus berkata bahwa setiap pria, yang menikahi wanita yang bercerai, sedang berzinah, maka setiap pria Israel selama ratusan tahun sebelumnya melakukan perzinahan yang, menurut Hukum Taurat Musa, menikahi wanita yang diceraikan. Nyatanya, setiap pria, dalam rombongan bersama Yesus pada hari itu, yang menikahi wanita yang diceraikan menurut Hukum Taurat Musa tiba-tiba merasa bersalah atas apa yang bukan salahnya satu menit sebelumnya, dan Yesus tentu telah mengubah aturan Allah saat itu. Lagipula, dengan merujuk pada kata-kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus bahwa menikahi orang yang bercerai bukanlah dosa, orang yang menikahi orang yang bercerai sebenarnya sedang melakukan dosa, dengan cara zinah.
Keseluruhan semangat dalam Alkitab membuat kita memuji pria yang menikahi wanita yang bercerai. Jika wanita itu jadi korban yang tak bersalah karena sikap egois bekas suaminya, saya salut kepada pria itu sama halnya dengan saya memuji pria yang menikahi janda, yang membuatnya ada di bawah pengawaan pria. Jika, wanita itu menanggung kesalahan karena perceraiannya sebelumnya, saya memujinya karena keserupaannya dengan Kristus dalam meyakini hal yang terbaik darinya, dan untuk kasih karunianya dalam berkorban untuk melupakan masa lalu dan menanggung resiko. Mengapa orang yang telah membaca Alkitab dan memiliki Roh Kudus di dalam dirinya berkesimpulan bahwa Yesus melarang seseorang untuk menikahi orang yang bercerai? Bagaimana pandangan tersebut sesuai dengan keadilan Allah, keadilan yang tak pernah menghukum orang karena menjadi korban, seperti kasus wanita yang diceraikan tanpa kesalahan di pihaknya? Bagaimana pandangan tersebut sesuai dengan pesan Injil, yang menawarkan pengampunan dan kesempatan lain bagi orang berdosa yang bertobat?
Kesimpulan (In Summary)
Alkitab secara konsisten berkata bahwa perceraian selalu melibatkan dosa bagi satu pihak atau kedua pihak. Allah tak pernah mau siapapun untuk bercerai, tetapi dengan penuh kasih memberi ketentuan bagi perceraian ketika terjadi amoralitas. Ia juga dengan penuh kasih memberikan ketentuan bagi orang yang diceraikan untuk menikah kembali.
Jika bukan karena perkataan Yesus tentang pernikahan kembali, maka tak ada pembaca Alkitab pernah berpikir bahwa pernikahan kembali adalah dosa (kecuali karena dua kasus yang sangat jarang terjadi di masa perjanjian lama dan karena satu kasus yang sangat jarang terjadi di masa perjanjian baru, yakni pernikahan kembali setelah seseorang diceraikan dari seorang Kristen sebagai seorang Kristen). Namun, kita telah dapatkan cara logis untuk mencocokkan perkataan Yesus tentang pernikahan kembali dengan ajaran Alkitab. Yesus tidak mengganti aturan pernikahan kembali dari Allah dengan aturan yang lebih ketat yang melarang pernikahan kembali pada tiap kejadian, sebagai aturan yang mustahil ditaati oleh orang yang sudah bercerai dan menikah lagi (bagaikan menegakkan benang basah), dan aturan yang membuat bingung dan menyebabkan orang lain melanggar aturan lain dari Allah. Malahan, Ia mendukung orang untuk memahami sikap munafiknya. Ia menolong orang yang meyakini bahwa orang itu tak pernah berzinah untuk memahami bahwa ia sedang berzinah dengan cara lain, yakni hawa-nafsu dan sikapnya yang liberal terhadap perceraian.
Sesuai ajaran Alkitab, pengampunan diberikan untuk orang berdosa yang bertobat, tak peduli apapun dosa yang dilakukannya, dan kesempatan kedua dan ketiga diberikan kepada orang berdosa, termasuk orang yang diceraikan. Tidak ada dosa dalam pernikahan kembali berdasarkan perjanjian baru, kecuali orang percaya yang diceraikan dari orang percaya lain, yang tak pernah terjadi karena orang percaya sejati tidak berbuat amoralitas, sehingga tak ada alasan untuk bercerai. Dalam peristiwa yang jarang terjadi itu, masing-masing pasangan harus tetap menyendiri atau saling berdamai.
[1]
Misalnya, perhatikan komentar seorang pendeta yang diceraikan yang dirinya terisah dari tubuh Kristus ketika ia menikah lagi. Ia berkata, “Lebih baik saya membunuh istri saya daripada menceraikannya. Setelah membunuhnya, saya bisa minta ampun, menerima pengampunan, menikah lagi secara sah, dan meneruskan pelayanan saya.”